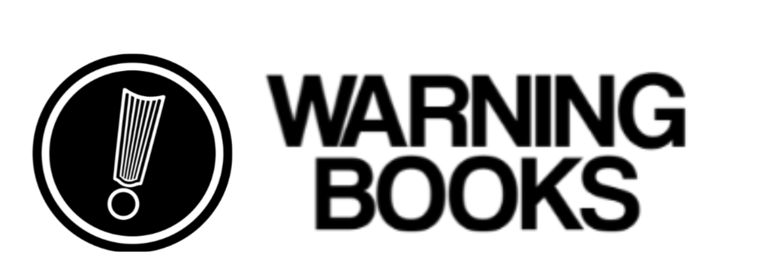Kepikiran Dangdut dan Hal-hal Pop Lainnya
Blog post description.
BOOKS


Judul: kepikiran dangdut dan hal-hal pop lainnya
Mahfud Ikhwan
Editor: Soni Triantoro
Cover: Bambang Nurdiansyah
Cetakan pertama, Januari 2024
ISBN 978-623-5879-09-3
263 halaman | 13 x 19 cm
Harga: 80.000
Sinopsis
Kumpulan tulisan musik dan budaya pop
“Jutaan orang di Indonesia kepikiran dangdut, hasilnya jogetan. Akademisi kepikiran dangdut, hasilnya rak baru perpustakaan. Mahfud Ikhwan kepikiran dangdut, hasilnya buku bagus.”
Link Pembelian
Kata Pengantar
KEPIKIRAN MAHFUD
Dalam sebuah ruang redaksi yang saya terlibat di dalamnya, diputuskan batalnya satu rencana memproduksi sebuah episode bincang-bincang antara musisi-musisi prominen dangdut koplo. Usulan mulanya adalah mendatangkan nama-nama seperti Denny Caknan, Ndarboy Genk, Inul Daratista, dll. Dibayangkan sang pengusul, mereka akan diundang duduk melingkar, bercakap-cakap mengenai pengalaman bertungkus lumus dengan musik koplo, laju kembang artistik, dan mungkin kisah-kisah menarik di balik lagu-lagunya.
Usulan itu gugur, ditikam sebuah argumen: ‘’Musik itu didengarkan. Tidak didiskusikan. Apalagi musik koplo. Tidak dibicarakan, tapi dijogetin saja.”
Jangan berpikir saya kemudian akan bertindak heroik menyangkal argumen itu, apalagi demi menyelamatkan jurnalisme musik atau ekosistem musik blahblahblah (?). Justru, saya yang paling sepakat.
Pengalaman saya mengelola media musik, media umum berlengkapkan kanal musik, ataupun media yang tidak sedia kanal musik sama sekali, hanya saling mempertegas kesimpulan bahwa ada banyak alasan kenapa media musik ambruk berantai di Indonesia. Angka bicara, artikel musik tidak selaku artikel lain. Beberapa kanal video bincang-bincang musik—bila tidak mengandung drama di dalamnya seperti Dhani vs Once, atau Ariel vs Andika (Peterpan)—hanya sanggup menarik views di angka puluhan sampai ratusan ribu. Ini kalah dari rataan dialog politik (tentu), atau perkontenan komika yang acap meraup angka jutaan. Bagaimana dengan buku atau literatur musik? Silakan tanyakan pada para penerbit (umum), tapi jangan bandingkan dengan fiksi pop atau buku self-help.
Sebetulnya, salah satu buntut dari kemajuan digital adalah menjungkarnya bukti-bukti kuantitatif kedigdayaan musik dangdut dan koplo. Yang dulunya hanya kebagian ‘’etalase’’ terbatas di medium-medium urban seperti televisi atau majalah, kini merajai platform-platform musik kiwari. Tidak tertandingi. Tak lagi harus turba ke angkot-angkot pantura atau bergerilya ke kota satelit untuk mengendus kebenaran bahwa dangdut dan koplo memang musik Indonesia.
Sayangnya, angka minat raksasa khalayak pada lagu-lagu dangdut dan koplo tidak bisa serta merta dikonversi menjadi views ketika yang dilakukan artisnya bukan bernyanyi/bermusik, tapi berpanjang lebar tentang sejarah, teknis musik, dll. Kalaupun ada wawancara berjuta penonton dengan nama-nama besar koplo, isinya tidak bicara musiknya—mungkin Anda akan langsung menemukan yang saya maksud jika mengetik kata kunci yang tepat di Youtube sekarang.
Inilah, kira-kira artian ‘’koplo tidak dibicarakan, dijogetin saja.’’
Tentu ini tak berangkat dari asumsi lama: penggemar dan pelaku dangdut itu berintelektualitas rendah, atau tidak berwawasan terhadap apa yang mereka lakukan sendiri. Toh, penggemar dangdut hari ini adalah irisan besar penggemar musik lain. Namun, sejujurnya, seingat-ingatnya, saya memang belum pernah menemukan orang yang betul-betul fasih bersenang-senang dengan dangdut sebagai sebuah wawasan musik.
Kecuali, dari yang saya kenal, ada satu orang:
.
Saya penggemar Mahfud Ikhwan sebagai pengarang. Saya tertegun dengan Kambing dan Hujan (2015) dan Dawuk (2017). Perihal kesusastraan, tak ada lagi keraguan dari saya untuknya, dan saya merasa Anda baiknya juga begitu.
Bagaimana Mahfud Ikhwan sebagai penulis dan pemerhati kultur pop? Yang ini Anda masih boleh ragu, tapi saya akan langsung yakinkan. Kira-kira separuh buku ini sudah pernah saya baca sebelumnya dalam bentuk artikel-artikel lepas. Dan saya menyukai sebagian besarnya.
Sepintas, saya ingat Remy Sylado, satu nama pegah yang cukup berimbang antara dua alam yang ditekuninya: kesusastraan dan kultur pop. Yup, penulis Puisi Mbeling, Ca-Bau-Kan, Kerudung Merah Kirmizy itu sekaligus redaktur majalah musik Aktuil dan bahkan seorang rocker. Sosok yang bisa dijadikan indikator identitas pergaulan kita, tergantung dari mana kita mengenal Remy duluan: 1) dari puisi dan novel, atau 2) dari lagu dan esai musiknya?
Kala mengarungi karya-karya Remy dalam beragam peran-profesi-wujudnya, saya merasa semuanya padu jadi satu. Beliau adalah penyair yang piawai menulis kritik musik, novelis yang ngeband, sepaket dengan musisi yang bersyair. Semua zat-zat kesenian, kesosokannya, eksentrismenya melebur, apapun yang ia lahirkan ke dunia.
Ini bagi saya agak membedakan dengan Mahfud. Ketika membaca buku bertajuk Kepikiran Dangdut ini, saya bisa menemukan jarak antara Mahfud sebagai seorang pengarang, dengan Mahfud sebagai seorang penulis esai musik – film yang antusias.
Dalam Kepikiran Dangdut, kita memang bisa memetik banyak pemahaman baru terkait latar belakang konsumsi Mahfud yang membentuk kebisaannya membenamkan musik dangdut ke dalam Dawuk, kasidah di Kambing dan Hujan, atau pop cengeng Malaysia di Ulid Tak Ingin ke Malaysia. Ia menyebut hubungan antara preferensi musik dan kepengarangannya ‘’seperti cetok dan meteran untuk tukang batu, atau sabit dan cangkul untuk petani.’’
Namun, kalaupun tidak peduli sama sekali dengan itu, Anda tetap bisa menikmati Mahfud Ikhwan sebagai penulis esai pop yang barangkali tulisannya sering tidak sengaja lewat di linimasa Twitter atau Facebook. Ia menyorongkan potongan pengalaman hidupnya, menjahitnya dengan wawasan dan kejelian. Mahfud menulis tanpa seakan-akan ingin mengubah dunia—atau menyelamatkan jurnalisme musik dan ekosistem musik blahblahblah (?). Ya sekadar seperti hendak bercerita saja, memamerkan seleranya. Nyaris sama seperti apa yang biasa kita coba lakukan.
Bedanya, selain keunikan preferensi musiknya—untuk ukuran orang-orang yang doyan mengekspose selera musik di medsos—Mahfud ialah pencerita yang lebih baik dari kita. Ambil contoh, artikel pertama di buku ini: ‘’Kepikiran Dangdut (Koplo)’’. Maksudnya hanya menjabarkan 8 alasan kenapa ia tidak bisa benci musik koplo, tapi hasilnya membuat saya merasa lebih paham musik koplo dibanding membaca satu-dua buku berbasis riset tentang topik sejenis.
Kalaupun kadang terasa asing, itu bukan imbas dari penulisan, tapi lebih pada adanya jarak antara kita dengan objek yang dibicarakannya. Gara-garanya, mungkin ya khazanah musik kesukaannya yang agak lain itu.
Pekerjaan rumah bagi pembaca, barangkali, mesti giat mengulik nama-nama yang disebutkan di buku ini. Karena bagi yang tidak familiar dengan musik dangdut lama, film India, atau ludruk (!), nama-nama seperti Cak Naryo, Poonam Dhillon, Kumar Sanu, Kartolo, Sersan Sapari, adalah ujian untuk membuat rendah hati dengan pengetahuan musik yang kita miliki. Setidaknya itu yang saya alami, selaku penyunting—dan yang secara semena-mena dituding sebagai kritikus di salah satu bab buku ini.
Saya selama ini menempatkan diri sebagai pendengar musik Top 40—saya mengetik ini sehabis pulang dari menonton tiket gratisan konser Charlie Puth—dan saya membebani diri sendiri dengan tugas memastikan ‘’akankah mereka yang jarang mendengar dangdut/koplo bisa nikmat membaca buku ini?’’
Mahfud sendiri agaknya tidak peduli dengan jawabannya—apakah bukunya akan tetap dibaca mereka yang tidak mengenali Rita Sugiarto atau Meggy Z? Tapi, saya pikir bisa.
Lagipula, adanya jarak itu tidak bisa kita perkarakan pada siapa-siapa. Mustahil menyalahkan Mahfud bila ia punya kuping melayu, gandrung pada Rhoma Irama, Zainuddin MZ, dan musik India. Ia sudah banyak-banyak menerangkan dari mana seleranya tumbuh, dan kita bisa menerimanya, karena ia menceritakannya dengan apik.
Dalam buku-buku kumpulan esai, mudah bagi kita biasanya untuk meraba-raba identitas penulisnya, berangkat dari gagasan atau cuplikan-cuplikan pengalaman yang diselipkan di tiap esai. Dalam Kepikiran Dangdut, kita malah tak harus meraba-raba. Mahfud sengaja mengedepankan identitasnya dalam artikel-artikelnya: bermasa kecil di desa Pantura Lamongan, dididik lebih sebagai orang Islam dibanding orang Jawa, tumbuh di tengah popularitas tayuban sebagai bagian dari ritual ibadah, mendengarkan Zainuddin MZ sampai khatam, akhirnya punya tape rekorder di SMA, tinggal berjarak 25 kilometer ke bioskop terdekat, tumbuh dikelilingi pendengar Rhoma Irama, menghafal ratusan lagu Soneta dan Awara dari toa hajatan, emaknya menyebut ‘’Bohemian Rhapsody’’ sebagai lagu wong edan, nonton bioskop pertama kali baru setelah menjadi tukang azan di masjid dekat Kali Code, dll.
Kita bisa anggap Kepikiran Dangdut adalah autobiografi seseorang yang tumbuh dari daerah pinggiran, dan kehausan hiburan.
Musik (film) India tidak datang kepada kami sebagai salah satu menu hidangan di meja makan restoran yang kami dipersilakan memilih sesukanya.
Untuk bocah-bocah yatim, tak lengkap, dan miskin macam kami ini, lagu (dan film) India nyaris memberi semua. Tentang dua kekasih yang terpisah? Mereka gudangnya. Ratapan seorang anak atas kepergian ibunya? Mereka jagonya. Kisah dua sahabat yang saling menyayangi lebih dari saudara? Mereka ahlinya. Tentang beratnya hidup dan pahitnya kemiskinan? Mereka tak ada bandingnya.
Tak pernah sebelumnya saya membaca buku kumpulan esai pop yang penulisnya begitu rela, mahir, dan memang punya banyak cerita bernilai untuk menunjukan darimana seleranya berasal. Cara menggambarkan akses-akses yang diperolehnya kadang malah lebih memikat daripada rasa penasaran terhadap musik yang sedang dibicarakannya.
Soneta yang saya hafal di luar kepala nyaris sepenuhnya saya dapat dari musik yang diputar oleh tetangga atau dari pengeras suara orang hajatan . Sedangkan kebanyakan lagu pop (cengeng) saya intip dari hasil menonton televisi orang lain.
Ini klise, tapi sepenuhnya benar: kemiskinan membuat musik yang saya sukai tak pernah betul-betul saya miliki, terutama secara fisik.
Pemahaman akan identitasnya itu kemudian mendukung Mahfud menyusun analisis-analisis tajam terhadap satu fenomena. Misalnya, artikel ‘’Dikem’’, sebuah obituari bagi belantika yang ditinggal wafat Didi Kempot. Cek saja, ada sederet obituari lain di internet, tapi Anda tidak akan menemukan yang seperti ‘’Dikem’’. Alih-alih fokus memprofilkan Didi Kempot, Mahfud justru menceritakan kehidupannya sendiri, dalam kerangka narasi berlatar lagu-lagu Didi Kempot.
Saya yakin, Mahfud bukan satu-satunya orang yang pernah dilarang nonton film karena bikin lupa ngaji. Bukan pula satu-satunya ‘’penyintas’’ situasi itu yang berakhir menjadi seseorang yang menekuni lirik-lirik Radiohead. Tapi caranya bertutur membuat ironi-ironi yang sebetulnya dilalui banyak remaja di negeri ini tersebut bisa menjelaskan lebih banyak gejala lainnya. Selera adalah pertarungan kelas, kita tahu. Tanpa menukil teori-teori, Kepikiran Dangdut bisa menguraikan bagaimana pertarungan itu berlangsung.
Di Jogja, saya mendapati musik-musik yang menemani saya tumbuh (dangdut, pop cengeng, kasidah, lagu-lagu India) bukan saja diremehkan, tapi juga menjadi asing. Kemunculan band-band berbasis kampus dengan musik humor/plesetan yang marak di awal 2000-an, yang sebagian besar menjadikan lagu dangdut sebagai objek leluconnya, misalnya, menegaskan keterasingan itu. Musik-musik itu terasa dan dipandang inferior, sebagaimana diri saya. Ia muncul, dinyanyikan, dinikmati, seringkali ditertawakan, ketika kelas menengah kota ingin menegaskan identitasnya—bahwa musik itu milik orang lain, bukan milik mereka.
Ini menggelisahkan dan menciptakan perasaan frustrasi pada diri saya. Rasa frustrasi itu coba saya salurkan lewat medium yang saya temukan pada saat kuliah di Jogja, yaitu menulis. Dan, saya pikir, dari sinilah proses “kenapa saya menulis tentang…” itu dimulai.
Namun, Mahfud tidak hanyut melulu bicara tentang dirinya sendiri. Dalam tugasnya menulis esai pop, ia tetap mengantungi aset wajib: wawasan pop yang mumpuni. Beberapa artikelnya menunjukan itu.
Tulisan ‘’Sheila dan Kita’’ adalah tulisan tentang Sheila on 7 terbaik yang pernah saya baca. Sedari dulu, saya sadar dan sepakat bahwa penulisan lirik Eross lebih bagus dibanding Ahmad Dhani (mari debat sampai mati!). Saya juga sudah pernah membaca tentang kehebatan lirik lagu “Sephia” membawa wacana kekasih gelap ke tingkatan lebih tinggi. Namun, mengambil kesimpulan bahwa lirik ‘’Perhatikan Rani’’ dan ‘’Tunggulah Aku di Jakarta’’ sebagai ekspresi desentralisasi dan anti-jakarta tidak pernah tebersit di kepala saya sebelumnya.
Atau artikel ‘’Tiara dan Nama-Nama Perempuan dalam Nyanyian Lelaki Putus Asa’’, membedah penggunaan nama-nama perempuan dalam lagu-lagu pop. Sesuatu yang mungkin pernah terlintas di batin kita, tapi tak pernah diwujudkan seserius dalam bentuk tulisan. ‘’Musik pop kita didirikan di atas nama-nama perempuan’’ adalah pernyataan emas. Di sini juga saya baru disadarkan apabila Sheila on 7 ternyata salah satu pelakunya: Rani, Niah, Disha, Lia, hingga Ibu Linda, dan tentu Sephia.
Tapi, tetap, andalan Mahfud memang nama-nama itu: Rhoma Irama, Zainuddin MZ, Didi Kempot. Analisisnya bahwa musikalitas Didi Kempot boleh jadi lebih berutang pada warisan musik pop melayu dibanding dangdut dalam artikel ‘’Pop Cengeng, Didi Kempot, dan Para Penerusnya” membuat saya yakin bahwa penggemar yang kritis patut diadu kapasitas telaahnya dengan barisan akademisi sekalipun.
Apalagi, musik dangdut, musik India, musik tradisi, dan genre-genre lain yang jarang muncul di percakapan snob urban sering kali hanya berakhir sebagai knowledge, dijadikan bahan studi berulang. Amat jarang literatur yang mengupas ranah musik itu dengan gaya yang lebih antusias, bersenang-senang, seperti skena memperlakukan musik metal, punk, indie pop, dll. Kalaupun ada, penulisnya mungkin bisa bersenang-senang, tapi pembacanya tidak, karena ditulis dengan buruk.
Jutaan orang di Indonesia kepikiran dangdut, hasilnya jogetan. Akademisi kepikiran dangdut, hasilnya rak baru perpustakaan. Mahfud Ikhwan kepikiran dangdut, hasilnya buku bagus.
.
Soni Triantoro
-Produser Eksekutif Narasi